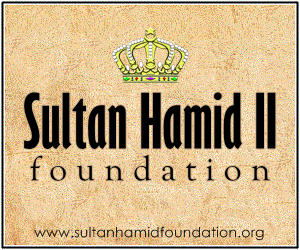Organisasi Advokat dan Federalisme Indonesia
http://ansharidimyati.blogspot.com/2016/05/organisasi-advokat-dan-federalisme.html
 |
| Advokat |
Riuh-rendah suara pengunjung terdengar dari sebuah ruangan kala agenda penabalan keabsahan organisasi advokat di Mahkamah Agung Indonesia dilakukan pada 24 Juni 2010 lalu. Islah nyaris tercapai antara kubu yang berseteru, yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tetapi perdebatan memanas. Upaya penyelesaian konfik, yang sudah berulang kali dilakukan, tak jua selesai.
Alih-alih mencapai kata sepakat, Mahkamah Agung justru dituding berpihak pada salah satu organisasi, yakni Peradi. Tak heran, KAI pun berang. Mahkamah Agung dinilai bersikap tak patut dengan hanya mengakui Peradi sebagai organisasi yang diakui. Mahkamah Agung hanya berwenang melantik berdasarkan undang-undang. Tak boleh ia berpihak atau mencampuri urusan rumah tangga organisasi advokat. Sebab organisasi profesi ini berdiri sama tinggi dan sejajar.
Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan yang isinya menginstruksikan kepala-kepala Pengadilan Tinggi di daerah-daerah agar tak melantik calon advokat yang tak berasal dari Peradi. Calon advokat di luar Peradi jelas mengeluh. Ini jelas bukan salah calon advokat yang ikut dalam organisasi di luar Peradi. Konflik organisasi ini hanya dalam tataran elite senior advokat yang duduk di pengurus organisasi.
Tindakan ini membuat para calon advokat yang berasal dari KAI dan organisasi lain tak dapat dilantik sebagai advokat. Ada kerugian materil dan imateril pasca pengakuan kedaulatan salah satu pihak yang berseteru itu. Sudah banyak biaya yang mereka keluarkan untuk pendidikan profesi tersebut, seperti uang untuk ujian dan segala macam. Pendidikan yang mereka tempuh pun runtuh seketika. Tak ada harapan bagi calon advokat karena Mahkamah Agung hanya mengakui organisasi yang di seberang itu. Dengan demikian, sangatlah jelas tak ada demokrasi di negara ini.
Sebenarnya, akar konflik ini bermula dari tumbuh kembangnya wadah kelembagaan organisasi advokat. Sejak dulu, memang tak kunjung ketemu ihwal konsep kelembagaan seperti apa yang dapat mewadahi profesi advokat dengan sebaik-baiknya. Yang terjadi adalah kemelut atas perbedaan kepentingan-kepentingan ‘politis’ untuk menguasai basis besar wadah profesi para pembela itu.
Fakta yang dapat dilihat adalah bahwa organisasi advokat sejak lama tidak tunggal, melainkan beragam (plural). Namun, penggabungan organisasi advokat untuk menjadi wadah tunggal dipaksakan oleh pemerintah. Bentuk tunggal itu dicetuskan pertama kali oleh Menteri Kehakiman, Ali Said, pada akhir 1970-an. Protes keras kemudian disuarakan oleh Ketua Umum Pesatuan Advokat Indonesia (Peradin). Peradin, merupakan sebuah organisasi advokat yang pertama kali berdiri di negara ini, di Jakarta, yakni pada 1963/1964.
Banyak advokat menolak penggabungan dalam wadah tunggal kala itu. Sebab, hal tersebut didasarkan pada perintah dari atas (pemerintah) (top down), bukan kehendak dari bawah (bottom up). Padahal, semua tindakan dalam organisasi advokat sepatutnya datang dari bawah berdasarkan aspirasi seluruh advokat melalui kongres atau musyawarah, yang dilakukan secara demokratis oleh faksi-faksi yang ada.
Pada 1985, terbentuklah organisasi advokat selain Peradin. Namanya Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Untuk mencegah organisasi advokat wadah tunggal seperti yang diinginkan pemerintah, kemudian muncul pula organisasi-organisasi advokat lainnya. Ikadin terpecah menjadi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Berlanjut dengan pecahnya AAI, lalu muncul pula Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), lalu pecah lagi dengan munculnya Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), dan seterusnya, sampai menjadi delapan organisasi advokat. Konsep wadah tunggal organisasi advokat gagal pada waktu itu.
Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, berdirilah Peradi sebagai wadah tunggal organisasi advokat pada 2005. Pemerintah kembali mengintervensi organisasi advokat (pasal 28 ayat 1 dan pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Delapan organisasi advokat yang telah ada pun dileburkan ke dalam satu organisasi.
Tapi, melebur tak berarti tunggal. Multitafsir atas undang-undang tersebut menuai protes keras banyak kalangan, dan membuat legitimasi Peradi pun goyah. Keberadaan Peradi dianulir karena tak melalui kongres (tidak demokratis) sesuai dengan amanat undang-undang. Dari konsolidasi yang dilakukan para advokat, kemudian dilakukanlah kongres. Dan terciptalah KAI untuk menandingi Peradi yang telah menyatakan dirinya sebagai wadah tunggal.
Hingga hari ini, terdapat beberapa organisasi yang menyatakan dirinya sebagai organisasi yang paling sah. Peradi, KAI, Peradin, Ikadin, dan beberapa lainnya. Namun, otoritas ada pada pemerintah, si pemberi legitimasi. Walau arah angin legitimasi itu ada pada Peradi, tapi tak dapat dibenarkan keberadaannya. Sebab, konflik internal advokat belumlah usai.
Konflik-konfik yang terjadi ini terkadang menjadi bahan tertawaan. Ada anekdot yang mengatakan bahwa “selesaikan masalahmu dulu, kemudian selesaikan masalah orang lain”. Bagaimana advokat dapat menyelesaikan kepentingan hukum masyarakat/klien, sedangkan untuk mengatur rumah tangga sendiri, yang berantakan itu, tak kunjung usai.
Negara dan Advokat: antara narasi tunggal dan pluralitas
“Diskriminasi nasionalisme merupakan keyakinan bahwa bangsa (sebuah wilayah komunitas) merupakan satu-satunya tujuan yang layak untuk dicita-citakan. Penegasan yang kerap memicu keyakinan bahwa ia menuntut loyalitas yang tak bisa dipertanyakan, apalagi dikompromikan,” demikian tulis Steven Grosby dalam bukunya Nationalism (2009).
Ketika keyakinan mengenai sebuah komunitas seperti tersebut di atas menjadi lebih utama, ia dapat mengancam kebebasan individu, dan tentu komunitas lainnya. Aksioma nasionalisme semacam itu pula yang kerap kali memandang faksi-faksi lain (dalam kehidupan sosial) sebagai lawan yang tak dapat dikompromikan. Ia menanamkan kebencian terhadap apa yang dipersepsikan pihak lain.
Di sisi lain, manusia adalah jenis makhluk yang mempertahankan simbol atau identitasnya. Sedangkan identitas yang dimiliki manusia itu bermacam ragam atau bersifat plural. Di Indonesia, negara memaklumatkan secara metaforis (simbolik) atas pengakuan terhadap pluralisme. Namun, pengakuan terhadap hak yang sama, kesederajatan, berserikatnya para komunitas, menjadi diskursus persoalan yang belum terpecahkan. Keadilan kolektif yang bersifat abstrak, jelas berbeda dengan keadilan antar golongan atau kelompok.
Persoalan itu pula yang tengah (selalu) dihadapi negara, hari ini. Kedewasaan politik negara menjadi barometer atas tegaknya identitas-identitas bangsa di dalamnya. Pemaksaan kehendak oleh negara untuk membuat satu entitas, dalam bentuk negara Kesatuan, merusak perbedaan-perbedaan yang telah ada sejak dulu. Tentu, Indonesia terjebak pada definisi bangsa dan negara. Yang sebelumnya beragam (plural), dipaksa menjadi seragam (tunggal).
Pengkultusan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara telah menerabas batas wilayah perbedaan komunitas. Ini tercantum pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Heterogenitas budaya dan pandangan hidup sosial serta merta diubah menjadi homogen. Akar persoalan tiap-tiap kasus di ‘negeri’ ini bermula dari sistem negara. Yang sepatutnya demokrasi, secara absurd, menjadi nomokrasi (kesatuan hukum).
Sikap hipokrit pemerintah menuai persoalan yang tak terselesaikan hingga hari ini. Mulai dari kasus hak ulayat masyarakat adat dan sertifikasi tanah oleh negara, faksi Islam yang mendorong agar dibuatnya regulasi syariah di wilayahnya, hasil pajak negara yang tak dinikmati rakyat secara kongkrit, dana perimbangan antara pusat dan daerah yang bagi hasilnya ditentukan bukan oleh pemilik tanah, sentralisasi dan desentralisasi, hingga keadilan kolektif yang bersifat abstrak.
Persoalan semacam itu pun dialami oleh profesi advokat. Ia menjadi korban atas buramnya sistem negara, buramnya bentuk negara, dan buramnya pandangan negara dalam mempersepsikan sebuah organisasi. Beribu-ribu kandidat advokat tak mendapatkan haknya untuk dilantik secara resmi sebagai advokat. Hal itu disebabkan “conflict of interest” organisasi-organisasi advokat, yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai organisasi yang paling sah di mata hukum/undang-undang.
Banyak pihak mengatakan bahwa organisasi advokat patut berwadah tunggal. Namun, data tak sesuai dengan fakta. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tak secara tegas mengatur bahwa organisasi profesi hukum tersebut harus berwujud tunggal.
Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”
Persepsi politis kalangan elit advokat menafsirkan pasal itu bahwa organisasi advokat “harus wadah tunggal”. Ketika ditilik ulang, tak satupun pasal/ayat menyebutkan harus berwadah tunggal. Jelas paradoks, karena tak diatur secara spesifik pengaturan wujud atau bentuk dari organisasi itu.
Fakta bahwa organisasi advokat itu plural, tak dapat ditepis. Sama halnya dengan entitas sosial masyarakat. Namun, pemerintah seakan tuli, bahwa akar persoalan ada pada sistem negara. Kalau bentuk negara tak dipaksakan tunggal, tak terseret pula dogma ketunggalan itu dalam ranah organisasi profesi. Itu fatal. Namun, untuk pemahaman atas kesederajatan dan hak berserikat faksi-faksi yang ada, tak diakomodir oleh negara.
Sepatutnya prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tak hanya hiasan kata mengikat dalam konstitusi. Ia ada karena berangkat dari kesamaan hak, sederajat, dan berdiri sama tinggi. Pun dengan organisasi. Setiap individu/kolektif, berhak untuk berserikat dan berkumpul, dan itu dijamin oleh konstitusi (pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945).
Jelas, tak cukup alasan pemerintah untuk menunggalkan sebuah lembaga/organisasi. Legitimasi persatuan organisasi itu muncul dari kesepakatan pihak-pihak di dalamnya (faksi-faksi advokat), bukan pihak ketiga (pemerintah). Dari itulah akan terukur independensi sebuah organisasi. Dan tak dapat dinafikan, bahwa negara itu pula sebuah organisasi.
Profesi Advokat, tak kunjung berdaulat
Secara terminologis, pengertian advokat didefinisikan sebagai orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.
Dalam undang-undang, advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dapat disimpulkan, bahwa advokat adalah merupakan profesi yang memberi jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/fee.
Sebutan untuk advokat bermacam ragam. Penasehat hukum, konsultan hukum, pengacara, kuasa hukum, menjadi varian sebutan orang yang memberi jasa bantuan hukum tersebut. Dalam bahasa Inggris, advokat disebut trial lawyer. Secara spesifik di Amerika dikenal sebagai attorney at law, atau di Inggris dikenal sebagai barrister. Peran yang diberikan oleh penasehat hukum di Amerika dikenal sebagai counsellor at law, atau di Inggris dikenal sebagai solicitor.
Selain itu, terdapat juga istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris yang melakukan pekerjaan bersifat nonlitigasi (di luar pengadilan), seperti: corporate lawyer, legal officer, legal councel, legal advisor, legal assistance.
Saat menjalankan tugas dan fungsinya, advokat berperan sebagai pendamping, pembela hak-hak hukum, pemberi advice hukum, pemberi bantuan hukum, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum, seorang advokat dapat melakukannya secara prodeo/pro bono publico (proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma/gratis – untuk masyarakat miskin), pun atas dasar mendapatkan honorarium/fee dari klien.
Bagi advokat, free profession (kebebasan profesi) cukup penting. Tak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yakni, terciptanya lembaga peradilan yang bebas (independent judiciary) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan rule of law dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.
Advokat dapat menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa tentang suatu perkara. Ia juga menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak-hak asasi manusia, dan memberi pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Jelas, profesi advokat sarat akan idealisme, yang menjadikan ia sebagai profesi mulia (officium nobile).
Namun, gelar yang disandang sebagai profesi terhormat/mulia itu kontras dengan pandangan masyarakat. Sebagian orang menganggap bahwa advokat adalah orang yang memutarbalikkan fakta; pekerjaan yang tak memiliki hati nurani; selalu membela orang yang salah; mendapatkan kesenangan di atas penderitaan orang lain; dan mendapatkan uang dengan menukar kebenaran dengan kebatilan.
Idealisme berbanding terbalik dengan kenyataan di permukaan. Barangkali hal itu merupakan sebagian dari kasus yang ditemukan. Namun, menjadi penting ketika ditilik kembali pemaknaan keberadaan advokat dalam dunia peradilan. Ia tak diciptakan sebagai agen komersialisasi hukum dalam memberi jasa hukum, pun tak diciptakan sebagai profesi ‘sampah’ dalam moralitas. Ia tercipta sebagai pembela hak-hak hukum bagi setiap orang yang mencari keadilan untuk menegakkan kebenaran.
Di Indonesia, profesi advokat tak kunjung berdaulat. Melulu intervensi dilakukan pemerintah kepada profesi ini. Pun dengan pengaturan mengenai apa dan siapa dirinya. Tak terlepas pula campur tangan pemerintah terhadap pengelolaan kelembagaan/organisasi advokat.
Banyak pihak salah kaprah menyebut advokat sebagai penegak hukum. Sebab, penegak hukum (law enforcement officials) hanyalah polisi dan jaksa, hakim adalah sebagai penegak keadilan. Sedangkan advokat adalah pembela, yang keberadaannya independen dan mandiri.
Secara historis, legitimasi organisasi penegak hukum diberikan pemerintah untuk hakim, jaksa, polisi, dan advokat dengan maksud untuk membentuk lembaga mereka masing-masing, dalam sebuah wadah tunggal. Pemerintah militer Orde Baru, pada 1970-an, membuat konsep catur wangsa. Konsep itulah yang menyeret profesi advokat sebagai penegak hukum. Kemudian hari, palebelan ini diabsahkan pada Undang-Undang Advokat (pasal 5 ayat 1).
Sedangkan di sisi lain, dalam pengertian teori sistem peradilan pidana terpadu (intergrated criminal justice system), advokat sebagai profesi hukum berseberangan keberadaannya dengan penegak hukum, seperti jaksa dan polisi. Secara teoretis, advokat tidak dikenal sebagai penegak hukum. Ia diartikan sebagai legal councel/lawyer, attorney, atau advocate. Hal ini dipertegas pula oleh Instrumen Internasional (Commentary pasal 1 United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials).
Terhadap status profesi advokat, kedaulatan sebagai profesi yang bebas dalam menentukan arah dan ruang gerak menjadi terkungkung dengan adanya campur tangan negara. Pun begitu dengan multitafsir status keberadaan organisasi advokat. Pemaksaan terhadap advokat untuk menjadi anggota dari organisasi advokat (wadah tunggal) yang dipaksakan pemerintah, merupakan pelanggaran hak konstitusional advokat yang tergabung dalam organisasi lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Undang-Undang Advokat sebetulnya telah mengatur soal eksistensi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri. Ia punya kewenangan untuk melakukan self governing, mengatur dan mengurus dirinya sendiri, tak dicampuri oleh pemerintah maupun keterlibatan lembaga negara lainnya.
Namun, kebebasan dan kemandirian advokat itu seakan menjadi tak berarti ketika ada keberpihakan Mahkamah Agung terhadap salah satu pihak dalam konflik internal advokat. Kedaulatan advokat dan organisasinya menjadi tak berdaya karena sebuah intervensi.
Negara sepatutnya memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negaranya yang berprofesi sebagai advokat, tentu tanpa melihat dari mana asal organisasinya. Sepatutnya pula, setiap orang yang berprofesi sebagai advokat bebas beracara di pengadilan, bebas mendapatkan sertifikasi dari faksi-faksi organisasi advokat yang ada, bebas memilih organisasi, dan bebas menentukan pilihan haknya sebagai advokat. Ini tak dapat dibatasi oleh negara.
Perlindungan terhadap perlakuan yang sama, yang seharusnya didapatkan advokat Indonesia tanpa melihat asal organisasinya, tercantum jelas dalam Pasal 9 IBA (International Bar Association) Standard for the Independence of the Legal Profession. Di situ dipertegas bahwa otoritas pemerintah atau pengadilan tak diperbolehkan menolak hak seorang advokat untuk berpraktek di pengadilan dalam suatu yurisdiksi atas nama kliennya.
Fakta berbanding terbalik. Ribuan advokat yang bukan berasal dari Peradi tak dapat berpraktek karena tak memperoleh pengakuan dari pengadilan. Hal ini merupakan sikap diskriminatif yang secara nyata telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia para advokat untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.
Campur tangan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara begitu jauh ke dalam, yang sebetulnya tak punya kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, yang absurd itu. Kemudian, kewenangan tersebut diterabas dengan menafsirkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, bahwa makna “satu-satunya” merupakan single bar association.
Federalisme, sebagai sebuah solusi atas konflik organisasi
Advokat senior, Frans Hendra Winarta, ikut gerah melihat kemelut organisasi advokat itu. Dia menerangkan bahwa akar persoalan ada pada bentuk organisasi (pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat) yang bersifat multitafsir. Sebaliknya, dengan dibentuknya sistem federasi sebagai sebuah solusi, akan meredam konflik internal. Sedangkan konsep wadah tunggal sudah gagal, dan tak perlu lagi dipaksakan.
“Dibentuk saja secara federasi, semua urusan diserahkan pada masing-masing organisasi. Tapi perlu dibentuk dewan sertifikasi untuk menghindari komersialisasi saat proses pelatihan dan ujian advokat,” ujar Frans di Jakarta.
Advokat senior yang juga governing board Komisi Hukum Nasional (KHN) itu pun menegaskan bahwa pasal 28 ayat (1) dapat ditafsirkan sebagai wadah tunggal (single bar association) atau bisa juga sebagai federasi (federation of bar association). Ketidakjelasan soal rumusan “satu-satunya wadah profesi” menjadi isu yang wajib dikaji ulang kembali secara materiil di Mahkamah Konstitusi.
Di dunia, dikenal tiga bentuk organisasi advokat. Pertama, Single Bar Association, yakni hanya ada satu organisasi advokat dalam suatu yurisdiksi (wilayah hukum dalam suatu negara). Kedua, Multi Bar Association, yakni terdapat beberapa organisasi advokat yang masing-masing tegak berdiri sendiri. Dan ketiga, Federation of Bar Associaton, yakni organisasi-organisasi advokat yang ada bergabung/bersatu dalam federasi di tingkat nasional. Dalam hal ini, sifat keanggotaannya adalah ganda, pada tingkat lokal dan nasional.
Ketiga bentuk organisasi advokat itu selayaknya sama dengan bentuk sebuah negara yang mewadahinya. Namun, menjadi penting untuk dikoreksi kembali, apakah bentuk negara dalam wilayahnya sudah tepat, atau hasil kepentingan politik sebagian pihak yang merugikan wilayah-wilayah komunitas di dalam negaranya.
Dalam konsep kenegaraan, bentuk negara menjadi pendasaran berjalannya sistem untuk menjalankan tujuan-tujuan dari bangsa/wilayah komunitas. Bentuk negara menyatakan struktur organisasi sebagai suatu keseluruhan, yang meliputi semua unsurnya atau negara dalam wujudnya sebagai suatu organisasi.
Indonesia pernah menjalankan dua konsep/bentuk negara pada saat transisi pasca berdaulat. Pertama adalah bentuk negara federasi (lihat Konsititusi Republik Indonesia Serikat) dan bentuk negara kesatuan atau unitaris.
Negara kesatuan (eenheidsstaat/unitaris) adalah negara yang bersusun tunggal, di mana ada satu pemerintahan yang memegang kekuasaan untuk menjalankan semua urusan wilayah-wilayah. Bersusun tunggal berarti bahwa dalam negara hanya ada satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu undang- undang dasar, dan satu lembaga legislatif.
Sedangkan negara federasi (bondstaat/federal/persatuan/serikat) adalah satu negara besar yang berfungsi sebagai pemerintahan keseluruhan dengan satu konstitusi federal, yang di dalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusinya sendiri-sendiri. Konstitusi federal mengatur batas-batas kewenangan keseluruhan (federal), sedangkan sisanya dianggap sebagai milik komunitas (negara bagian).
Sistem negara Indonesia hari ini adalah unitaris/kesatuan, dan inilah yang menyeret organisasi advokat untuk harus berwujud tunggal. Heterogenitas atas faksi-faksi yang ada dalam tubuh organisasi advokat dinafikan karena bentuk negara yang jelas salah. Bentuk negara kesatuan, yang sentral dan tunggal, sepatutnya hanya berada pada wilayah komunitas kecil dan homogen. Ia tak dapat berdiri objektif ketika dihadapkan pada macam-macam corak yang beragam. Bahkan, pada kondisi yang beragam, ia dapat ditafsirkan sedang melakukan penjajahan.
Konsep negara federal pernah diterapkan di Indonesia, kala bersatunya negara-negara atau komunitas-komunitas yang telah ada di Kepulauan Melayu ini. Namun, singkat waktu, karena arogansi politik dan militer sebagian pihak (unitaris), konsep negara itu pun diganti.
Di sisi lain, keberagaman faksi-faksi yang ada di Indonesia sebetulnya menjadi modal dasar untuk membenarkan sistem federal sebagai sebuah konsep organisasi. Federalisme akan mempertegas kedaulatan kelompok-kelompok yang ada, yang berada pada sebuah wadah besar. Hak-hak berserikat juga akan terakomodir dengan baik ketika kedaulatan faksi-faksi itu pun diakui.
Konsep federal sangat penting untuk organisasi profesi advokat di Indonesia. Ia barangkali merupakan pilihan terbaik, dan patut dipertimbangkan untuk kita coba dalam menerapkan sistem tersebut. Hal serupa juga selayaknya diamini oleh negara.
Jika kita mengakui bahwa Indonesia adalah plural, sistem federal adalah konsep yang tepat untuk kedua organisasi itu. Federal untuk organisasi advokat dan federal untuk organisasi besar seperti Indonesia.
Alih-alih mencapai kata sepakat, Mahkamah Agung justru dituding berpihak pada salah satu organisasi, yakni Peradi. Tak heran, KAI pun berang. Mahkamah Agung dinilai bersikap tak patut dengan hanya mengakui Peradi sebagai organisasi yang diakui. Mahkamah Agung hanya berwenang melantik berdasarkan undang-undang. Tak boleh ia berpihak atau mencampuri urusan rumah tangga organisasi advokat. Sebab organisasi profesi ini berdiri sama tinggi dan sejajar.
Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan yang isinya menginstruksikan kepala-kepala Pengadilan Tinggi di daerah-daerah agar tak melantik calon advokat yang tak berasal dari Peradi. Calon advokat di luar Peradi jelas mengeluh. Ini jelas bukan salah calon advokat yang ikut dalam organisasi di luar Peradi. Konflik organisasi ini hanya dalam tataran elite senior advokat yang duduk di pengurus organisasi.
Tindakan ini membuat para calon advokat yang berasal dari KAI dan organisasi lain tak dapat dilantik sebagai advokat. Ada kerugian materil dan imateril pasca pengakuan kedaulatan salah satu pihak yang berseteru itu. Sudah banyak biaya yang mereka keluarkan untuk pendidikan profesi tersebut, seperti uang untuk ujian dan segala macam. Pendidikan yang mereka tempuh pun runtuh seketika. Tak ada harapan bagi calon advokat karena Mahkamah Agung hanya mengakui organisasi yang di seberang itu. Dengan demikian, sangatlah jelas tak ada demokrasi di negara ini.
Sebenarnya, akar konflik ini bermula dari tumbuh kembangnya wadah kelembagaan organisasi advokat. Sejak dulu, memang tak kunjung ketemu ihwal konsep kelembagaan seperti apa yang dapat mewadahi profesi advokat dengan sebaik-baiknya. Yang terjadi adalah kemelut atas perbedaan kepentingan-kepentingan ‘politis’ untuk menguasai basis besar wadah profesi para pembela itu.
Fakta yang dapat dilihat adalah bahwa organisasi advokat sejak lama tidak tunggal, melainkan beragam (plural). Namun, penggabungan organisasi advokat untuk menjadi wadah tunggal dipaksakan oleh pemerintah. Bentuk tunggal itu dicetuskan pertama kali oleh Menteri Kehakiman, Ali Said, pada akhir 1970-an. Protes keras kemudian disuarakan oleh Ketua Umum Pesatuan Advokat Indonesia (Peradin). Peradin, merupakan sebuah organisasi advokat yang pertama kali berdiri di negara ini, di Jakarta, yakni pada 1963/1964.
Banyak advokat menolak penggabungan dalam wadah tunggal kala itu. Sebab, hal tersebut didasarkan pada perintah dari atas (pemerintah) (top down), bukan kehendak dari bawah (bottom up). Padahal, semua tindakan dalam organisasi advokat sepatutnya datang dari bawah berdasarkan aspirasi seluruh advokat melalui kongres atau musyawarah, yang dilakukan secara demokratis oleh faksi-faksi yang ada.
Pada 1985, terbentuklah organisasi advokat selain Peradin. Namanya Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Untuk mencegah organisasi advokat wadah tunggal seperti yang diinginkan pemerintah, kemudian muncul pula organisasi-organisasi advokat lainnya. Ikadin terpecah menjadi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Berlanjut dengan pecahnya AAI, lalu muncul pula Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), lalu pecah lagi dengan munculnya Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), dan seterusnya, sampai menjadi delapan organisasi advokat. Konsep wadah tunggal organisasi advokat gagal pada waktu itu.
Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, berdirilah Peradi sebagai wadah tunggal organisasi advokat pada 2005. Pemerintah kembali mengintervensi organisasi advokat (pasal 28 ayat 1 dan pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Delapan organisasi advokat yang telah ada pun dileburkan ke dalam satu organisasi.
Tapi, melebur tak berarti tunggal. Multitafsir atas undang-undang tersebut menuai protes keras banyak kalangan, dan membuat legitimasi Peradi pun goyah. Keberadaan Peradi dianulir karena tak melalui kongres (tidak demokratis) sesuai dengan amanat undang-undang. Dari konsolidasi yang dilakukan para advokat, kemudian dilakukanlah kongres. Dan terciptalah KAI untuk menandingi Peradi yang telah menyatakan dirinya sebagai wadah tunggal.
Hingga hari ini, terdapat beberapa organisasi yang menyatakan dirinya sebagai organisasi yang paling sah. Peradi, KAI, Peradin, Ikadin, dan beberapa lainnya. Namun, otoritas ada pada pemerintah, si pemberi legitimasi. Walau arah angin legitimasi itu ada pada Peradi, tapi tak dapat dibenarkan keberadaannya. Sebab, konflik internal advokat belumlah usai.
Konflik-konfik yang terjadi ini terkadang menjadi bahan tertawaan. Ada anekdot yang mengatakan bahwa “selesaikan masalahmu dulu, kemudian selesaikan masalah orang lain”. Bagaimana advokat dapat menyelesaikan kepentingan hukum masyarakat/klien, sedangkan untuk mengatur rumah tangga sendiri, yang berantakan itu, tak kunjung usai.
Negara dan Advokat: antara narasi tunggal dan pluralitas
“Diskriminasi nasionalisme merupakan keyakinan bahwa bangsa (sebuah wilayah komunitas) merupakan satu-satunya tujuan yang layak untuk dicita-citakan. Penegasan yang kerap memicu keyakinan bahwa ia menuntut loyalitas yang tak bisa dipertanyakan, apalagi dikompromikan,” demikian tulis Steven Grosby dalam bukunya Nationalism (2009).
Ketika keyakinan mengenai sebuah komunitas seperti tersebut di atas menjadi lebih utama, ia dapat mengancam kebebasan individu, dan tentu komunitas lainnya. Aksioma nasionalisme semacam itu pula yang kerap kali memandang faksi-faksi lain (dalam kehidupan sosial) sebagai lawan yang tak dapat dikompromikan. Ia menanamkan kebencian terhadap apa yang dipersepsikan pihak lain.
Di sisi lain, manusia adalah jenis makhluk yang mempertahankan simbol atau identitasnya. Sedangkan identitas yang dimiliki manusia itu bermacam ragam atau bersifat plural. Di Indonesia, negara memaklumatkan secara metaforis (simbolik) atas pengakuan terhadap pluralisme. Namun, pengakuan terhadap hak yang sama, kesederajatan, berserikatnya para komunitas, menjadi diskursus persoalan yang belum terpecahkan. Keadilan kolektif yang bersifat abstrak, jelas berbeda dengan keadilan antar golongan atau kelompok.
Persoalan itu pula yang tengah (selalu) dihadapi negara, hari ini. Kedewasaan politik negara menjadi barometer atas tegaknya identitas-identitas bangsa di dalamnya. Pemaksaan kehendak oleh negara untuk membuat satu entitas, dalam bentuk negara Kesatuan, merusak perbedaan-perbedaan yang telah ada sejak dulu. Tentu, Indonesia terjebak pada definisi bangsa dan negara. Yang sebelumnya beragam (plural), dipaksa menjadi seragam (tunggal).
Pengkultusan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara telah menerabas batas wilayah perbedaan komunitas. Ini tercantum pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Heterogenitas budaya dan pandangan hidup sosial serta merta diubah menjadi homogen. Akar persoalan tiap-tiap kasus di ‘negeri’ ini bermula dari sistem negara. Yang sepatutnya demokrasi, secara absurd, menjadi nomokrasi (kesatuan hukum).
Sikap hipokrit pemerintah menuai persoalan yang tak terselesaikan hingga hari ini. Mulai dari kasus hak ulayat masyarakat adat dan sertifikasi tanah oleh negara, faksi Islam yang mendorong agar dibuatnya regulasi syariah di wilayahnya, hasil pajak negara yang tak dinikmati rakyat secara kongkrit, dana perimbangan antara pusat dan daerah yang bagi hasilnya ditentukan bukan oleh pemilik tanah, sentralisasi dan desentralisasi, hingga keadilan kolektif yang bersifat abstrak.
Persoalan semacam itu pun dialami oleh profesi advokat. Ia menjadi korban atas buramnya sistem negara, buramnya bentuk negara, dan buramnya pandangan negara dalam mempersepsikan sebuah organisasi. Beribu-ribu kandidat advokat tak mendapatkan haknya untuk dilantik secara resmi sebagai advokat. Hal itu disebabkan “conflict of interest” organisasi-organisasi advokat, yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai organisasi yang paling sah di mata hukum/undang-undang.
Banyak pihak mengatakan bahwa organisasi advokat patut berwadah tunggal. Namun, data tak sesuai dengan fakta. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tak secara tegas mengatur bahwa organisasi profesi hukum tersebut harus berwujud tunggal.
Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”
Persepsi politis kalangan elit advokat menafsirkan pasal itu bahwa organisasi advokat “harus wadah tunggal”. Ketika ditilik ulang, tak satupun pasal/ayat menyebutkan harus berwadah tunggal. Jelas paradoks, karena tak diatur secara spesifik pengaturan wujud atau bentuk dari organisasi itu.
Fakta bahwa organisasi advokat itu plural, tak dapat ditepis. Sama halnya dengan entitas sosial masyarakat. Namun, pemerintah seakan tuli, bahwa akar persoalan ada pada sistem negara. Kalau bentuk negara tak dipaksakan tunggal, tak terseret pula dogma ketunggalan itu dalam ranah organisasi profesi. Itu fatal. Namun, untuk pemahaman atas kesederajatan dan hak berserikat faksi-faksi yang ada, tak diakomodir oleh negara.
Sepatutnya prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tak hanya hiasan kata mengikat dalam konstitusi. Ia ada karena berangkat dari kesamaan hak, sederajat, dan berdiri sama tinggi. Pun dengan organisasi. Setiap individu/kolektif, berhak untuk berserikat dan berkumpul, dan itu dijamin oleh konstitusi (pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945).
Jelas, tak cukup alasan pemerintah untuk menunggalkan sebuah lembaga/organisasi. Legitimasi persatuan organisasi itu muncul dari kesepakatan pihak-pihak di dalamnya (faksi-faksi advokat), bukan pihak ketiga (pemerintah). Dari itulah akan terukur independensi sebuah organisasi. Dan tak dapat dinafikan, bahwa negara itu pula sebuah organisasi.
Profesi Advokat, tak kunjung berdaulat
Secara terminologis, pengertian advokat didefinisikan sebagai orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.
Dalam undang-undang, advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dapat disimpulkan, bahwa advokat adalah merupakan profesi yang memberi jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/fee.
Sebutan untuk advokat bermacam ragam. Penasehat hukum, konsultan hukum, pengacara, kuasa hukum, menjadi varian sebutan orang yang memberi jasa bantuan hukum tersebut. Dalam bahasa Inggris, advokat disebut trial lawyer. Secara spesifik di Amerika dikenal sebagai attorney at law, atau di Inggris dikenal sebagai barrister. Peran yang diberikan oleh penasehat hukum di Amerika dikenal sebagai counsellor at law, atau di Inggris dikenal sebagai solicitor.
Selain itu, terdapat juga istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris yang melakukan pekerjaan bersifat nonlitigasi (di luar pengadilan), seperti: corporate lawyer, legal officer, legal councel, legal advisor, legal assistance.
Saat menjalankan tugas dan fungsinya, advokat berperan sebagai pendamping, pembela hak-hak hukum, pemberi advice hukum, pemberi bantuan hukum, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum, seorang advokat dapat melakukannya secara prodeo/pro bono publico (proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma/gratis – untuk masyarakat miskin), pun atas dasar mendapatkan honorarium/fee dari klien.
Bagi advokat, free profession (kebebasan profesi) cukup penting. Tak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yakni, terciptanya lembaga peradilan yang bebas (independent judiciary) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan rule of law dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.
Advokat dapat menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa tentang suatu perkara. Ia juga menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak-hak asasi manusia, dan memberi pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Jelas, profesi advokat sarat akan idealisme, yang menjadikan ia sebagai profesi mulia (officium nobile).
Namun, gelar yang disandang sebagai profesi terhormat/mulia itu kontras dengan pandangan masyarakat. Sebagian orang menganggap bahwa advokat adalah orang yang memutarbalikkan fakta; pekerjaan yang tak memiliki hati nurani; selalu membela orang yang salah; mendapatkan kesenangan di atas penderitaan orang lain; dan mendapatkan uang dengan menukar kebenaran dengan kebatilan.
Idealisme berbanding terbalik dengan kenyataan di permukaan. Barangkali hal itu merupakan sebagian dari kasus yang ditemukan. Namun, menjadi penting ketika ditilik kembali pemaknaan keberadaan advokat dalam dunia peradilan. Ia tak diciptakan sebagai agen komersialisasi hukum dalam memberi jasa hukum, pun tak diciptakan sebagai profesi ‘sampah’ dalam moralitas. Ia tercipta sebagai pembela hak-hak hukum bagi setiap orang yang mencari keadilan untuk menegakkan kebenaran.
Di Indonesia, profesi advokat tak kunjung berdaulat. Melulu intervensi dilakukan pemerintah kepada profesi ini. Pun dengan pengaturan mengenai apa dan siapa dirinya. Tak terlepas pula campur tangan pemerintah terhadap pengelolaan kelembagaan/organisasi advokat.
Banyak pihak salah kaprah menyebut advokat sebagai penegak hukum. Sebab, penegak hukum (law enforcement officials) hanyalah polisi dan jaksa, hakim adalah sebagai penegak keadilan. Sedangkan advokat adalah pembela, yang keberadaannya independen dan mandiri.
Secara historis, legitimasi organisasi penegak hukum diberikan pemerintah untuk hakim, jaksa, polisi, dan advokat dengan maksud untuk membentuk lembaga mereka masing-masing, dalam sebuah wadah tunggal. Pemerintah militer Orde Baru, pada 1970-an, membuat konsep catur wangsa. Konsep itulah yang menyeret profesi advokat sebagai penegak hukum. Kemudian hari, palebelan ini diabsahkan pada Undang-Undang Advokat (pasal 5 ayat 1).
Sedangkan di sisi lain, dalam pengertian teori sistem peradilan pidana terpadu (intergrated criminal justice system), advokat sebagai profesi hukum berseberangan keberadaannya dengan penegak hukum, seperti jaksa dan polisi. Secara teoretis, advokat tidak dikenal sebagai penegak hukum. Ia diartikan sebagai legal councel/lawyer, attorney, atau advocate. Hal ini dipertegas pula oleh Instrumen Internasional (Commentary pasal 1 United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials).
Terhadap status profesi advokat, kedaulatan sebagai profesi yang bebas dalam menentukan arah dan ruang gerak menjadi terkungkung dengan adanya campur tangan negara. Pun begitu dengan multitafsir status keberadaan organisasi advokat. Pemaksaan terhadap advokat untuk menjadi anggota dari organisasi advokat (wadah tunggal) yang dipaksakan pemerintah, merupakan pelanggaran hak konstitusional advokat yang tergabung dalam organisasi lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Undang-Undang Advokat sebetulnya telah mengatur soal eksistensi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri. Ia punya kewenangan untuk melakukan self governing, mengatur dan mengurus dirinya sendiri, tak dicampuri oleh pemerintah maupun keterlibatan lembaga negara lainnya.
Namun, kebebasan dan kemandirian advokat itu seakan menjadi tak berarti ketika ada keberpihakan Mahkamah Agung terhadap salah satu pihak dalam konflik internal advokat. Kedaulatan advokat dan organisasinya menjadi tak berdaya karena sebuah intervensi.
Negara sepatutnya memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negaranya yang berprofesi sebagai advokat, tentu tanpa melihat dari mana asal organisasinya. Sepatutnya pula, setiap orang yang berprofesi sebagai advokat bebas beracara di pengadilan, bebas mendapatkan sertifikasi dari faksi-faksi organisasi advokat yang ada, bebas memilih organisasi, dan bebas menentukan pilihan haknya sebagai advokat. Ini tak dapat dibatasi oleh negara.
Perlindungan terhadap perlakuan yang sama, yang seharusnya didapatkan advokat Indonesia tanpa melihat asal organisasinya, tercantum jelas dalam Pasal 9 IBA (International Bar Association) Standard for the Independence of the Legal Profession. Di situ dipertegas bahwa otoritas pemerintah atau pengadilan tak diperbolehkan menolak hak seorang advokat untuk berpraktek di pengadilan dalam suatu yurisdiksi atas nama kliennya.
Fakta berbanding terbalik. Ribuan advokat yang bukan berasal dari Peradi tak dapat berpraktek karena tak memperoleh pengakuan dari pengadilan. Hal ini merupakan sikap diskriminatif yang secara nyata telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia para advokat untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.
Campur tangan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara begitu jauh ke dalam, yang sebetulnya tak punya kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, yang absurd itu. Kemudian, kewenangan tersebut diterabas dengan menafsirkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, bahwa makna “satu-satunya” merupakan single bar association.
Federalisme, sebagai sebuah solusi atas konflik organisasi
Advokat senior, Frans Hendra Winarta, ikut gerah melihat kemelut organisasi advokat itu. Dia menerangkan bahwa akar persoalan ada pada bentuk organisasi (pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat) yang bersifat multitafsir. Sebaliknya, dengan dibentuknya sistem federasi sebagai sebuah solusi, akan meredam konflik internal. Sedangkan konsep wadah tunggal sudah gagal, dan tak perlu lagi dipaksakan.
“Dibentuk saja secara federasi, semua urusan diserahkan pada masing-masing organisasi. Tapi perlu dibentuk dewan sertifikasi untuk menghindari komersialisasi saat proses pelatihan dan ujian advokat,” ujar Frans di Jakarta.
Advokat senior yang juga governing board Komisi Hukum Nasional (KHN) itu pun menegaskan bahwa pasal 28 ayat (1) dapat ditafsirkan sebagai wadah tunggal (single bar association) atau bisa juga sebagai federasi (federation of bar association). Ketidakjelasan soal rumusan “satu-satunya wadah profesi” menjadi isu yang wajib dikaji ulang kembali secara materiil di Mahkamah Konstitusi.
Di dunia, dikenal tiga bentuk organisasi advokat. Pertama, Single Bar Association, yakni hanya ada satu organisasi advokat dalam suatu yurisdiksi (wilayah hukum dalam suatu negara). Kedua, Multi Bar Association, yakni terdapat beberapa organisasi advokat yang masing-masing tegak berdiri sendiri. Dan ketiga, Federation of Bar Associaton, yakni organisasi-organisasi advokat yang ada bergabung/bersatu dalam federasi di tingkat nasional. Dalam hal ini, sifat keanggotaannya adalah ganda, pada tingkat lokal dan nasional.
Ketiga bentuk organisasi advokat itu selayaknya sama dengan bentuk sebuah negara yang mewadahinya. Namun, menjadi penting untuk dikoreksi kembali, apakah bentuk negara dalam wilayahnya sudah tepat, atau hasil kepentingan politik sebagian pihak yang merugikan wilayah-wilayah komunitas di dalam negaranya.
Dalam konsep kenegaraan, bentuk negara menjadi pendasaran berjalannya sistem untuk menjalankan tujuan-tujuan dari bangsa/wilayah komunitas. Bentuk negara menyatakan struktur organisasi sebagai suatu keseluruhan, yang meliputi semua unsurnya atau negara dalam wujudnya sebagai suatu organisasi.
Indonesia pernah menjalankan dua konsep/bentuk negara pada saat transisi pasca berdaulat. Pertama adalah bentuk negara federasi (lihat Konsititusi Republik Indonesia Serikat) dan bentuk negara kesatuan atau unitaris.
Negara kesatuan (eenheidsstaat/unitaris) adalah negara yang bersusun tunggal, di mana ada satu pemerintahan yang memegang kekuasaan untuk menjalankan semua urusan wilayah-wilayah. Bersusun tunggal berarti bahwa dalam negara hanya ada satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu undang- undang dasar, dan satu lembaga legislatif.
Sedangkan negara federasi (bondstaat/federal/persatuan/serikat) adalah satu negara besar yang berfungsi sebagai pemerintahan keseluruhan dengan satu konstitusi federal, yang di dalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusinya sendiri-sendiri. Konstitusi federal mengatur batas-batas kewenangan keseluruhan (federal), sedangkan sisanya dianggap sebagai milik komunitas (negara bagian).
Sistem negara Indonesia hari ini adalah unitaris/kesatuan, dan inilah yang menyeret organisasi advokat untuk harus berwujud tunggal. Heterogenitas atas faksi-faksi yang ada dalam tubuh organisasi advokat dinafikan karena bentuk negara yang jelas salah. Bentuk negara kesatuan, yang sentral dan tunggal, sepatutnya hanya berada pada wilayah komunitas kecil dan homogen. Ia tak dapat berdiri objektif ketika dihadapkan pada macam-macam corak yang beragam. Bahkan, pada kondisi yang beragam, ia dapat ditafsirkan sedang melakukan penjajahan.
Konsep negara federal pernah diterapkan di Indonesia, kala bersatunya negara-negara atau komunitas-komunitas yang telah ada di Kepulauan Melayu ini. Namun, singkat waktu, karena arogansi politik dan militer sebagian pihak (unitaris), konsep negara itu pun diganti.
Di sisi lain, keberagaman faksi-faksi yang ada di Indonesia sebetulnya menjadi modal dasar untuk membenarkan sistem federal sebagai sebuah konsep organisasi. Federalisme akan mempertegas kedaulatan kelompok-kelompok yang ada, yang berada pada sebuah wadah besar. Hak-hak berserikat juga akan terakomodir dengan baik ketika kedaulatan faksi-faksi itu pun diakui.
Konsep federal sangat penting untuk organisasi profesi advokat di Indonesia. Ia barangkali merupakan pilihan terbaik, dan patut dipertimbangkan untuk kita coba dalam menerapkan sistem tersebut. Hal serupa juga selayaknya diamini oleh negara.
Jika kita mengakui bahwa Indonesia adalah plural, sistem federal adalah konsep yang tepat untuk kedua organisasi itu. Federal untuk organisasi advokat dan federal untuk organisasi besar seperti Indonesia.
Media: Lentera Timur